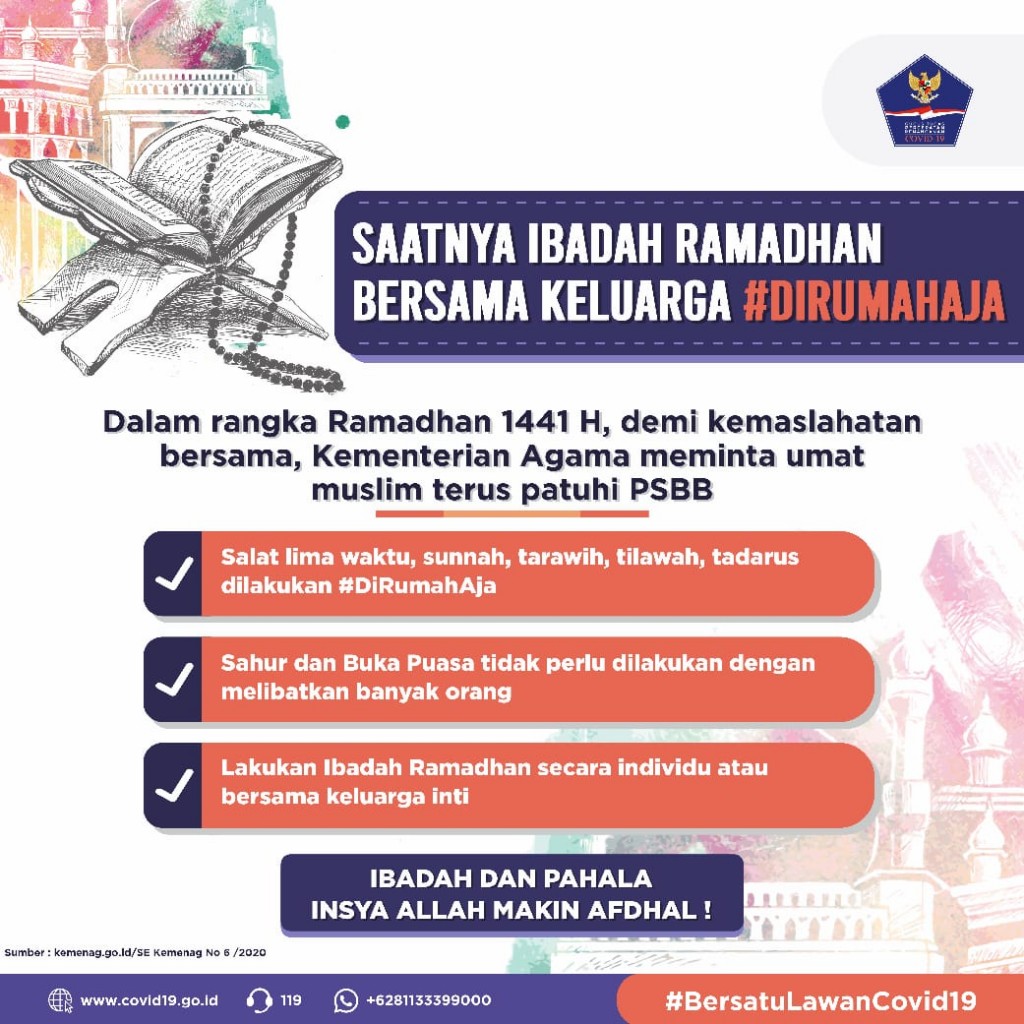Wednesday 03 January 2018
kary marunduh
2842
‘Hiperrealitas Media’
Ruang Parodi Realitas
Oleh: Kary Marjuni Marunduh
Memahami pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mempertanyakan pemberitaan media yang terkesan melebih-lebihkan realitas yang sesungguhnya. Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga mengatakan “informasi melalui media terkadang pahit seperti jamu, kadang terasa pahit dan bisa juga sebagai vitamin yang menyehatkan”. Pernyataan ini berangkat dari kritik Presiden Jokowi terhadap pemberitaan media yang terkesan melebih-lebihkan realitas yang sesungguhnya terjadi. Melalui judul-judul pemberitaan yang bombastis sehingga dapat meruntuhkan optimisme publik, karakter dan etos kerja. Seharusnya menurut Presiden Jokowi, pemberitaan media mampu membangun optimisme dan karakter serta etos kerja di tengah era kompetisi sekarang ini, jangan sebaliknya memberikan informasi yang justru menimbulkan pesimisme bahkan pemberitaan yang hanya mengejar rating yang hanya mengangkat hal-hal yang sensasional semata. Pertanyaan besarnya adalah: benarkah media lagi menampilkan hiperrealitas dengan memparodikan realitas? Ataukah sesungguhnya media memang lagi menampilkan wujud nyata dari realitas natural?
Bisa jadi, media memang lagi memerankan parodi yang mengingkari realitas ketika belantara simulakra mengerangkengnya. Media sepertinya memainkan citra hiperrealistik menjadi nafas dari setiap acara yang digelar media demi dramatisasi yang dihasilkan. Realitas yang dimunculkan adalah realitas yang penuh kamuflase dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasa. Kasus sidang di Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) yang menyidangkan Setya Novanto atas laporan pengaduan dari Sudirman Said, gemerlapnya sidang Pansus Pelindo yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka, gaduhnya konflik KPK dengan Polri, Revisi UU KPK, demonstrasi buruh, eksekusi mati bandar narkoba, live pernihakan Raffi Ahmad, perseteruan Ahok dengan DPRD DKI, dan lain-lain semua tidak lepas dari rekayasa dramatik. Tidak heran jika program berita di televisi menggeser acara hiburan (sinetron) sebagaimana yang dilansir Kompas (14/1/10).
Jean Baudrillard, dalam The Gulf War did not take Place, menggambarkan medan perang rekaan (simulacrum of war) yang ditampilkan media. Menurutnya, citraan media tentang perang tidak sepenuhnya merepresentasi realitas perang yang sesungguhnya. Ladang minyak yang terbakar, gedung-gedung yang runtuh, jeritan menyayat hati, gelimang dan cipratan darah, sandera yang meratap dalam takut –semua bisa disimulasikan di dalam studio televisi dengan lingkungan artifisial dan tokoh-tokoh palsu. Bandingkan juga dengan ungkapan kemarahan Noam Chomsky yang menabalkan media sebagai the trum of violence dikarenakan media melakukan dramatisasi dalam pemuatan isi media. Media menjadi panggung pementasan dramaturgi yang dilumuri adegan-adegan sarat kamuflase. Realitas dalam media adalah realitas terkonstruksi (constructed reality) yang dikemas sedemikian rupa sehingga tak ada lagi bentang demarkasi antara yang faktual dan yang artifisial.
Suara senada juga diteriakkan seorang kritikus media, Herbert I. Schiller dalam esainya “Manipulating Heart and Mind” (1992): ”Teater utama operasi untuk perang informasi adalah televisi.” Dalam perang media, para ahli ilusi mengaduk-aduk realitas perang melalui fotografi, pemilihan sudut pandang (angle), penentuan subjek liputan yang sensasional, dan efek dramatisasi dalam proses pemberitaan. Fenomena di atas oleh Idy Subandy mengkategorikan dalam “sirnanya komunikasi empatik”. Hiperrealitas media memicu media menjelma agen yang mempertontonkan nilai estetis semu yang jauh dari realitas (nature reality). Istilah hiperrealitas media digunakan oleh Jean Boudrillard untuk menjelaskan terjadinya perekayasaan (distorsi) dalam media (Piliang, 2004:141). Media yang menampilkan estetika hiperrealitas akan mengemas informasi menjadi tontonan (spectacle). Artinya, semakin dramatis sebuah realitas ditampilkan, maka media berhasil mengimprovisasikan realitas.
Kemampuan media untuk memanipulasi realitas -menjadi tontonan- meniscayakan media menjelma sebagai arena simulasi. Oleh Boudrillard menyebut media sebagai The desire of simulation (bandingkan Mark Poster. The Second Media Age. Cambridge:Polity Press, 1998. P. 16). Baudrillard mengenalkan konsep simulakrum yang diidentikan dengan beberapa sinonim: counterfeit, dupicate, facsimile, model, reproduction, dan xerox. Baudrillard membedakan simulakrum dengan simulasi. Simulasi adalah proses radikalisasi dari simulakrum. Simulasi, menurut Baudrillard, adalah sebentuk pengingkaran terhadap realitas sejati yang sering disebut sebagai “…meleburnya salinan (copy) dan aslinya (original). Dalam simulasi tak ada batas lagi antara yang asli dengan yang tiruan (duplikasi). Bahkan dalam kondisi tertentu yang tiruan nampak lebih asli dari yang asli (hiperreality). Pandangan Baudrillard yang terkesan tragik dalam melihat realitas media dan kerinduannya pada moda komunikasi langsung (face to face communication) menyebabkannya sering ditabalkan sebagai penganut konservatisme nostalgik.
Sebagaimana kemasygulan Martin Esslin, seorang ahli dan praktisi media terkemuka dalam karyanya, Age of Television (1982), mengungkapkan bahwa kehadiran media TV telah menggiring cara berpikir manusia untuk memahami realitas menjadi ilusi, dan sebaliknya, khayalan menjadi realitas. Penikmat TV akan terbawa pola imajinasinya sesuai dan seturut dari apa yang ditampilkan berdasarkan keinginan pemilik media. Menurut Esslin, TV telah berperan dalam menjelmakan warna buram budaya masyarakat karena daya simbolismenya yang sanggup mereduksi dan memanipulasi realitas menjadi fragmen-fragmen yang terberai dari kehidupan. Demikian juga, seperti yang dikatakan oleh Walter Truett Anderson (1990:127) dalam Reality Isn’t What it used to be, bahwa media mengambil bahan baku dari pengalaman dan mengemasnya dalam bentuk cerita; kemudian media memaparkan kembali cerita itu kepada kita, dan kita menyebutnya sebagai realitas.
Televisi tidak sekedar kanal katarsis bagi hiburan, tetapi ia berusaha menawarkan ideologinya sendiri (medium is the message). Ideologi yang terkonstruk saat media bertaut dengan kepentingan ekonomi kapitalis (market). Naluri kapitalistik media memompa hasratnya untuk melakukan komodifikasi berbagai realitas hidup yang disubstitusi oleh citra artifisial. Media memungut segala peristiwa yang tercecer menjadi sebentuk tontonan yang memiliki daya magnetik untuk mengundang para pengiklan (modal). Program filantropis yang menonjolkan aspek kemanusiaan pun tidak lagi steril dari kepentingan ekonomi media (economic interest). Air mata yang meleleh dalam reality show, tangis buncah dalam acara dzikir keagamaan, sikap altruistik pada sang liyan, mengada sebagai adegan dari skenario dramaturgis yang diciptakan media. Munculnya berbagai program “reality show” di televisi menguatkan asumsi itu. Hampir semua yang dipertontonkan televisi saat ini adalah program artifisial yang penuh rekayasa. Tepuk tangan di acara olah raga, kemeriahan di acara variety show, tangis dan tawa di acara kuis, bahkan drama di acara reality show yang mengangkat urusan pribadi, sebagian besar juga hasil rekayasa (Kompas.com). Seandainya Marshall McLuhan dihadapkan dengan fenomena ini, mungkin dia akan buru-buru merevisi tesisnya tentang Understanding Media yang mendaulat media sebagai the Exstensions of Man sebab media –saat ini- adalah arena pengingkaran realitas natural (natural reality).
Perkembangan teknologi (media) memang membawa konskuensi signifikan bagi tumbuhnya rasa yang tidak memiliki kerangka faktual. Pada tahun 1988, John Walker, misalnya, mengusulkan sebuah proyek “Pintu Masuk ke dalam Cyberspace” dengan moto Reality is Not Enough Any More (Hikmat Budiman, 2002:81). Kehadiran teknologi media (TV, komputer, internet dsb) mendorong orang mulai mempertimbangkan berbagai realitas lain di luar realitas kehidupan sehari-hari. Teknologi baru yang mempertontonkan hiperrealitas, simulasi, dan virtual reality tidak bisa lagi dimaknai sebagai cermin realitas sosial melainkan sebagai “others”. Realitas sehari-hari (the paramount reality) adalah salah satu bentuk realitas dalam dunia kehidupan yang kita alami dalam kondisi terjaga sepenuhnya dan bersifat self evident yang kita terima apa adanya. Berbeda dengan realitas-realitas lain yang hadir sebagai wilayah-wilayah makna yang terbatas dan berhingga (finite province of meaning).
Dengan demikian, kritik Presiden Jokowi di awal tulisan ini mendapatkan ruang pembenarannya. Sebab, hiperrealitas media menjadi ancaman serius bagi eksistensi media sebagai ruang publik yang seharusnya tidak terjebak pada kepalsuan imagologi. Dengan kepalsuan telah meruntuhkan optimism, karakter dan etos kerja publik yang terus berjuang di atas kepalsuan realitas. Rekayasa imagologi oleh media sama saja dengan pengingkaran idealitas media sebagai ruang publik sekaligus spasi yang menyuburkan dialektika dan perbincangan beragam unsur dalam realitas kehidupan.
Revitalisasi ruang publik di media menjadi keniscayaan untuk melepaskan media dari jerat hiperrealitas. Kedaulatan publik untuk mendapatkan informasi yang benar harus segera diupayakan melalui proses civic education. Herry Priyono menawarkan rute revitalisasi ruang publik melalui: pertama, melakukan reedukasi agency (agency reeducation), sebuah upaya pembentukan kesadaran publik yang berfokus pada peningkatan kualitas publik (agency). Reedukasi ini bertujuan untuk membentuk etos dan keutamaan warga (civic virtues), keberadaban publik (public civility) serta kohesi komuniter, yang semuanya merupakan alasan adanya ruang publik. Ruang publik yang terbuka luas disadari sangat rentang dengan masuknya informasi media yang cenderung memparodikan realitas. Reedukasi agency juga penting sebagai pintu masuk penyadaran publik (public awarness) agar tidak larut dan terjebak dalam dunia hiperrealitas media yang akan menggiring mereka dalam katastropi sejarah.
Kedua, melalui kebijakan publik (public policy). Perumusan kebijakan publik terkait dengan peran negara sebagai penjaga ruang publik. Keterlibatan negara diperlukan dalam proyek revitalasi ruang publik sebagai kekuatan legitimasi. Langkah ini dilakukan melalui pelibatan badan publik (public agency), yang memiliki netralitas dari tarikan ektrem negara dan pasar, sebagai penggerak (steering power) proses revitalisasi. Menurut Herry, sebenarnya ada mekanisme yang dapat ditempuh untuk merevitalisasi ruang publik tanpa pelibatan badan publik, yaitu dengan politik komunitarian. Akan tetapi pengalaman yang pernah terjadi, pendekatan ini buntu karena persoalan legalitas.
Ketiga, melalui reedukasi selera pasar. Ikhtiar ini dilakukan untuk menciptakan keberadaban publik (public civility) yang berkenaan dengan upaya memperbaiki selera pasar meskipun hal ini sepintas nampak sebagai utopia karena pasar merupakan ruang kebebasan selera (freedom if taste). Akan tetapi, pasar seharusnya menunjukkan eksistensinya di atas logika profit media yang mengutamakan kepentingan ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, selera pasar harus dipuaskan dengan pemberitaan media yang menampilan realitas yang sesungguhnya, jauh dari kamuflase realitas.
Melihat berbagai fenomena yang dihadirkan media saat ini, revitalisasi ruang publik mendesak untuk segera dilakukan demi menghidupkan kembali ruang publik yang telah mati sekaligus membebaskan media dari jerat kekuatan hegemonik: ekonomi kapitalistik dan politik pencitraan. Pertanyaan besarnya adalah: Mungkinkah itu diimplementasikan?


.jpg)